Ketika lagu kebangsaan Amerika Serikat âThe Star-Spangled Bannerâ berkumandang sebelum pertandingan olahraga American Football akhir Agustus lalu, ada pemandangan menarik di antara para pemain serta penonton yang menyanyikan lagu kebangsaan tersebut dengan khidmat. Colin Kaepernick, seorang pemain quarter back NFL (liga nasional untuk olahraga American Football di AS) dari tim San Francisco 49ers memilih untuk tetap duduk sepanjang lagu kebangsaan itu dinyanyikan seluruh isi stadium.
Bukan hanya sekali, Kaepernick mengulangi hal tersebut di pertandingan selanjutnya. Di kesempatan lain, ia juga terlihat menggunakan kaos kaki bermotif polisi dengan kepala babi, sebuah kritik akan fenomena korupsi di kepolisian Amerika. Sontak saja, kelakuan tersebut mendapat respon yang beragam dari seluruh publik Amerika, termasuk para politisi, penonton, petinggi NFL hingga beberapa rekan setimnya. Bahkan, calon presiden Amerika dari partai Republican, Donald Trump, juga turut berkomentar bahwa Caepernick seharusnya mencari negara lain yang cocok dengannya ketimbang melecehkan lagu kebangsaan.
Selidik punya selidik, tindakan Kaepernick tersebut adalah buntut dari rasa frustasinya terhadap tindakan penindasan dan pelecehan rasial terhadap komunitas Afrika-Amerika (African-American) di seluruh penjuru Amerika. Memang dalam beberapa bulan terakhir, penangkapan tak berdasar, penembakan serta sentimen negatif terhadap komunitas Afrika-Amerika sedang memuncak.
âAku tidak akan berdiri dan menunjukkan rasa kebanggaan terhadap negara yang masih menindas orang kulit hitam dan orang non-kulit putih lainnya,â terang Kaepernick mengenai tindakannya tersebut. âSekali lagi, aku bukan orang anti-Amerika, aku melakukan ini karena aku ingin Amerika menjadi tempat yang lebih baik.â Tambahnya lagi.
Jika Donald Trump saja âbolehâ melecehkan secara eksplisit orang-orang imigran serta lawan politiknya, mengapa tindakan Kaepernick yang memperjuangkan keadilan ini justru dihujat?
Perlawanan yang dimaksud di sini merupakan sebuah upaya nir-kekerasan yang diinisiasi oleh pihak di luar institusi politik dan bebas dari embel-embel kepentingan politis. Dalam sejarah modern AS, memang bukan kali ini saja olahraga menjadi sebuah platform yang digunakan sebagai wadah perlawanan terhadap ketidakadilan. Kejadian yang paling tenar tentu saja ketika dua atlet lari Amerika, Tommie Smith dan John Carlos, mengepalkan tangan ke udara saat pemutaran lagu kebangsaan AS di Olimpiade 1968 sebagai simbol pergerakan sosial komunitas Afrika-Amerika kala itu.
Lalu ada pula petinju legendaris Muhammad Ali yang kala itu rela kehilangan lisensi tinju-nya karena menentang habis-habisan program wajib militer warga AS untuk dikirim menuju medan perang di Vietnam. Di akhir milenium pula Ali dan beberapa pesohor lainnya tergabung dalam gerakan sosial multinasional Jubilee 2000, yang bertujuan untuk menghapus hutang-hutang negara berkembang, dimana ia dan Bono, vokalis grup band U2 berhasil mendesak pemerintah Amerika saat itu untuk mengucurkan dana jutaan dollar ke negara berkembang untuk mengatasi pandemik HIV/AIDS.
Berkaitan dengan olahraga basket, perlawanan sempat muncul di seantero liga NBA beberapa tahun silam ketika pemilik Los Angeles Clippers, Donald Sterling, mengeluarkan komentar bernada rasis terhadap pemain keturunan Afrika-Amerika. Sontak saja, banyak tim, termasuk Cleveland Cavaliers, Los Angeles Clippers, Houston Rockets dan Portland Trailblazers sepakat menggunakan aksesoris basket bernuansa hitam selama pertandingan sebagai bentuk protes.
Usaha ini berbuah manis ketika NBA akhirnya menjatuhkan larangan seumur hidup untuk tidak terlibat dalam kegiatan basket bagi Sterling, yang membuatnya harus merelakan kepemilikan Clippers beralih ke tangan Steve Ballmer, mantan CEO Microsoft.
Pada kesempatan lain, empat sekawan; Lebron James, Carmelo Anthony, Dwyane Wade dan Chris Paul bersuara lantang di acara tahunan ESPY Award 2016 untuk memprotes keras perlakuan kekerasan polisi terhadap komunitas Afrika-Amerika di Louisiana.
âKami berdiri di sini untuk memperjuangkan peran kami dalam mempersatukan komunitas (di AS),â ujar Chris Paul mengenai keputusannya beserta tiga kawannya untuk mengambil tindakan sebagai simbol perlawanan.
Masih banyak lagi kisah perlawanan sosial di bagian dunia lain yang memanfaatkan olahraga sebagai platform untuk meningkatkan kekuatan perlawanan tersebut. Apalagi dengan popularitas yang dimiliki oleh atlet, sikap mereka bisa menjadi suatu katalis untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai ketimpangan-ketimpangan sosial yang ada di sekitar mereka.
Bagaimana dengan Indonesia? Saya sendiri belum menyaksikan banyak perlawanan yang memanfaatkan bidang olahraga. Mungkin, gerakan âDepok Butuh GOR Basketâ yang mulai muncul akhir-akhir ini merupakan salah satu pengejewantahan konsep ini.
Walaupun âhanyaâ menuntut pembangunan GOR basket, hal ini merupakan suatu refleksi yang penting karena tuntutan itu menggambarkan permasalahan bahwa, mungkin saja, pemerintah Depok selama ini justru lebih giat membangun pusat perbelanjaan modern ataupun hal-hal lainnya yang kurang merefleksikan kebutuhan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut.
Toh, pembangunan GOR juga nantinya akan berdampak positif terhadap pemberdayaan masyarakat di Depok karena pasti akan ada banyak kegiatan positif yang dilakukan di situ.
Keterlibatan figur publik serta beberapa atlet basket nasional, dikombinasikan dengan kampanye melalui sosial media, merupakan elemen yang mungkin nanti akan memperkuat efek dari gerakan ini. Entah nantinya akan berhasil atau tidak untuk menyadarkan mereka yang masih kerap bermuka tebal di kantor-kantor pemerintahan sana, gerakan âDepok Butuh GOR Basketâ ini bisa kita pandang secara positif sebagai suatu perlawanan dari kelompok masyarakat yang menuntut ketidakadilan dan keganjilan yang terjadi di sekitar kita, serta sebagai penegasan bahwa dunia olahraga juga dapat dimanfaatkan untuk membantu kesuksesan sebuah perlawanan.(*)
























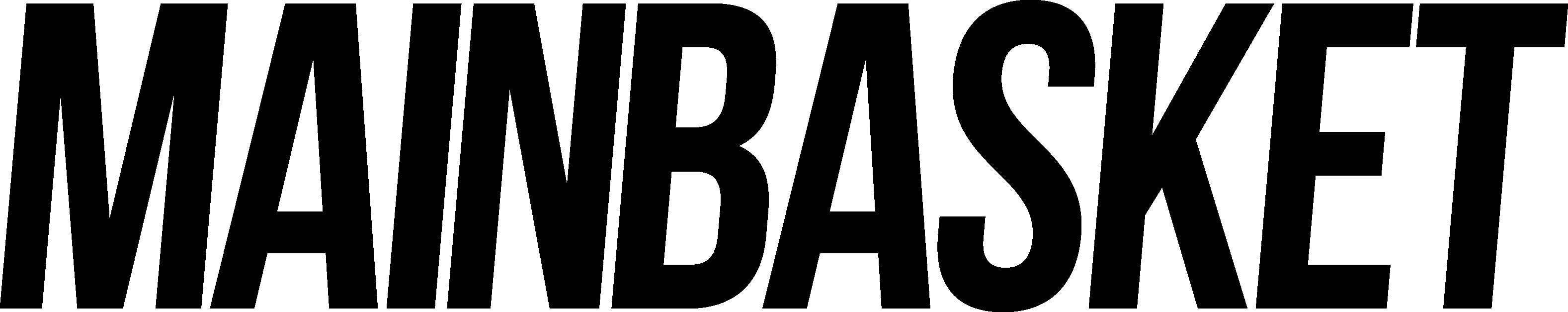




 0822 3356 3502
0822 3356 3502