Hari ini, 6 September 2016, Honda DBL Camp akan mengumumkan 12 campers putra dan putri terbaiknya. Mereka berhak menjadi skuat DBL All Star dan berangkat ke Amerika Serikat (AS) bulan November nanti.
Selain 24 pemain, Honda DBL Camp juga akan memilih empat pelatih yang akan mendampingi mereka. Masing-masing dua pelatih putra dan putri.
Kemarin, pada hari ketiga DBL Camp, seorang teman menghampiri saya. Ia menanyakan perihal komentar seseorang di instagram @dblindonesiaofficial.
Saat itu, saya tidak tahu apa yang teman saya itu maksudkan. Ia kemudian membuka salah satu unggahan di @dblindonesiaofficial yang memuat komentar tersebut. Komentarnya menarik.
âBagaimana DBL bisa memilih dgn fair dan membuang 124 pemain dalam waktu yg sangat singkat? Apa yakin dr antara 124 yg terbuang nanti tidak ada yg lebih bagus skill nya dr 100 yg terpilih. Apa semua campers di berikan waktu yg sama untuk nunjukin skill? Terlalu pendek wkt seleksi, no fair selection #justsayingâ
âIya tahu bahwa ini ajang kompetisi. Krn sy kenal bbrp campers terdahulu, dan mereka ksh tahu saya, ada yg bilang "saya hanya dikasih kesempatan 1 mnt nunjukin skill, stlh itu disuruh duduk dan tdk dipanggil lagi". 1 bulan, pasti lebih bagus dr pada hanya 3 hari - utk buang 124 pemain. Dr 224 pemain menjadi 24 pemain di akhir camp day yg 6 hari itu? Apa yakin bisa seleksi yg terbaik? Hebat sekali klo yakin bisa seleksi 24 yg terbaik dr 224 dlm 6 hari. Meskipun tiap campers hrsâ
âMeskipun tiap campers telah kerja keras dan push to the limit, yakin ini fair selection dimana tiap campers dpt kesempatan yg sama?â
Hmm, baiklah.
Dari komentar panjang tersebut, saya mencoba menyimpulkannya menjadi satu pertanyaan menggelitik. Setidaknya bagi saya sendiri.
âMampukah para pelatih di DBL Camp memilih 24 pemain terbaik (12 putra, 12 putri) hanya dalam tempo empat hari?â
Selama ini, saya sering menganggap bahwa sistem yang dijalankan DBL Camp adalah sistem yang sangat baik. Pertanyaan di atas membuka peluang bahwa sistem sebaik apa pun pasti ada celanya.
Saya hampir selalu mengikuti DBL Camp. Hanya absen dua kali. Empat di antaranya, saya aktif ikut berdiskusi dengan para pelatih WBA dan para pemain dan pelatih âwaktu itu- NBL Indonesia dalam memilih siapa saja 24 pemain yang terpilih masuk ke skuat DBL All Star. Saya juga ikut aktif ketika DBL Camp masih bersama para pelatih NBA. (Sistemnya sama).
Selain empat kali mengikuti secara langsung proses pemilihan 24 pemain All Star, saya selalu mengikuti DBL Camp dari pinggir lapangan. Berdialog dengan para pelatih dan para peserta.
Dari pengalaman tersebut, saya mencoba menjawab pertanyaan di instagram @dblindonesiaofficial di atas.
Jawaban saya adalah 'ya' dan 'tidak'. Dan saya akan jelaskan kenapa âyaâ alias bisa memilih 24 pemain dalam empat hari, dan âtidakâ bisa memilih pemain terbaik dalam waktu tersebut.
Ya, bisa.
Memilih 24 pemain terbaik DBL Camp bukanlah perkara sulit. Mudah!
Teramat mudah terkadang.
Sebelum mereka menuju Surabaya, kurang lebih 250 pemain yang hadir di Honda DBL Camp adalah 10 pemain terbaik di kota masing-masing (25 kota tahun ini). Berkumpul di Surabaya, mereka berkompetisi menunjukkan permainan terbaik mereka.
Pada hari pertama, para campers menjalani beberapa uji coba. Yang awal benar adalah beep test, tinggi lompatan dan lain-lain. Dari sini saja, para penilai sudah bisa mendapatkan gambaran awal kasar tentang para pemain.
Mana yang punya stamina atau kekuatan terbaik, dan mana yang âwell, lompatannya tinggi. Kelihatannya sepele. Namun di akhir, faktor-faktor kecil ini bisa memberi dampak signifikan terhadap terpilihnya seorang pemain ke dalam skuat All Star atau tidak.
Lalu ada stasiun-stasiun fundamental basketball. Ada delapan stasiun. Namun dari delapan stasiun tersebut, ada beberapa stasiun yang langsung membongkar kemampuan bermain seseorang.
Misalnya, stasiun rebound-run-rebound dan one-on-one. Dua stasiun ini menunjukkan kualitas kemampuan dan kemauan seorang pemain. Dari sana saja, kita sudah bisa melihat mana pemain berbakat dan punya niat tinggi, dan mana yang tidak.
Pada setiap stasiun, setiap pemain tidak hanya mendapat satu kali kesempatan. Mereka akan melakukannya berkali-kali. Jadi ada kesempatan bagi para pemain untuk memperlihatkan kemampuannya di beberapa kesempatan dan juga pelatih untuk menilai mereka di beberapa kali tampilan.
Mungkinkah seorang pelatih keliru menilai?
Mungkin saja.
Tetapi berdasarkan pengalaman bermain para pelatih yang bertahun bahkan belasan dan puluhan tahun, kecil rasanya kemungkinan mereka akan meleset. Wong saya saja yang hanya pengamat biasa bisa melihat mana yang punya skill dan mana yang skill-nya pas-pasan.
Ini fakta kecil. Di setiap akhir camp, saya dan beberapa teman suka iseng menulis nama-nama pemain yang kiranya akan terpilih. Percaya atau tidak, pilihan kami sebagian besar tepat. Kalau keliru, paling satu-dua pemain saja.
Sebelumnya, mereka yang terpilih ke 50 besar adalah yang skill-nya di atas rata-rata. Untuk masuk ke 24 besar, mereka harus beradu melawan sesama yang memiliki kemampuan kurang lebih setara.
Karena kemampuan teknik bermain basket sudah dianggap cukup setara, 50 pemain ini mulai naik level. Level materi basketnya meningkat. Mereka mulai mendapat pola-pola bermain sederhana. Pola-pola ini kembali tersebar di beberapa stasiun. Ada stasiun yang berisi materi screen and roll, defense, cutting, dan lain-lain.
Nah, di sinilah basket menunjukkan bahwa ia (seperti halnya cabang olahraga lain) membutuhkan kecerdasan para pemainnya.
Pemain cerdas sekaligus memiliki kemampuan bermain yang baik akan mudah melewati setiap stasiun. Beberapa pemain, membutuhkan usaha keras untuk memahami maksud para pelatih. Kasarnya, proses seleksi mulai masuk ke sesi kecerdasan bermain.
Dalam beberapa kesempatan, pola-pola yang terlihat sederhana sangat sulit dieksekusi oleh beberapa pemain. Mereka kebingungan. Skill bagus jadi hampir tak berguna. Pelatih akan lebih menyukai pemain yang memiliki kemampuan standar, tetapi bisa bermain efektif.
Pada hari ketiga, terpilihlah 24 pemain terbaik selama camp. Ujiannya tambah berat. Salah seorang pelatih mengatakan kepada saya bahwa pada level ini, dibutuhkan seorang pemain yang kuat secara fisik sekaligus mental, tanpa melupakan apa yang sudah didapat di dua hari sebelumnya. Berat. Sangat berat!
Kuat fisik dalam arti sebenarnya. Dua hari latihan tanpa henti, dan semakin keras di dua hari berikutnya.
Kalau fisik tak kuat, seorang pemain niscaya tumbang! Atau minimal melemah. Ketika fisik melemah, banyak kualitas permainan akan menurun. Para pemain mungkin ada yang tak sadar, tetapi basket adalah olahraga yang memamerkan semuanya. Turn over, terlambat defense, tembakan air ball, memegang pinggang, terduduk lama dan lain-lain adalah indikasi-indikasi kecil melemahnya fisik seorang pemain.
Kekuatan mental juga akan berbicara. Hanya mental-mental yang kokoh yang mau terus berusaha pantang menyerah. Berkompetisi melawan pemain-pemain yang sama gigihnya merebut satu tempat di skuat All Star, berjibaku dengan mereka bahkan seolah tak mau menyerah ingin saling menyingkirkan.
Mental! Mental! Mental! Kalau tidak punya mental kuat, pemain akan roboh.
Pemain dengan skill hebat akan mulai bermain egois. Akan mulai kehilangan fokus. Tidak lagi mengikuti instruksi. Mudah melakukan kesalahan dan lain-lain. Pelatih berpengalaman mudah mendeteksi ini.
Saya sering melihat para pelatih sampai kesal dengan mengganti mereka walau baru satu menit bermain. Kadang ada yang ditegur ke tengah lapangan.
Tentu saja si pelatih lebih dulu meminta permainan dihentikan. Saya bahkan pernah melihat, karena gemas, sang pelatih menunjuk kepala dan dada si pemain seolah berkata, âMain pakai hati dan otakmu!â
Pada level ini, DBL Camp menunjukkan kualitasnya. 24 campers berjuang mati-matian! Banyak yang melakukan kesalahan. Tetapi lebih banyak lagi yang berusaha untuk tidak mengulangnya. Tidak sedikit pemain yang mengabaikan tanda-tanda kelelahan yang amat sangat. Yakin bahwa selepas jam enam sore, mereka punya 12 jam untuk istirahat.
Yang menyerah? Ada. Ada yang api semangatnya terlihat meredup. Mereka tanpa sadar mulai mengerek bendera putih. Biasanya, di ruang penilaian, ketika rapat, para pelatih dengan mudah sepakat untuk mencoret mereka.
Akhirnya, di ujung hari keempat, 12 nama putra dan putri terpilih. Ujung dari proses intensif selama empat hari.
Biasanya, bahkan selalu, inilah bagian terberat bagi peserta DBL Camp. Mereka yang sudah terpilih sih akan merasa senang luar biasa. Tetapi mereka yang sudah merasa memberikan segalanya tetapi tidak terpilih, tentu merasakan tikaman yang dalam.
Saya, dari tepi panggung pengumuman bisa merasakannya. Hampir tidak mungkin menutupi raut kecewa karena nama mereka tak dipanggil Azrul Ananda di akhir Camp.
Bukti lain bahwa memilih pemain hebat di DBL Camp tidaklah sedemikian beratnya juga pernah terjadi pada dua kasus âyang menurut saya unik. Kasus ini terjadi pada nama Rizal Falconi dan Agustin Elya Gradita Retong.
Rizal adalah campers tahun 2010. Badannya kurus ceking bak lidi. Pemain ini sangat layak dipandang sebelah mata. Rizal bahkan tak mampu melewati hari pertama karena muntah-muntah dan kehabisan tenaga.
Hari kedua dan ketiga dijalani Rizal dengan semangat. Ketika tak banyak orang melihat potensi Rizal, para pelatih Australia justru melihat sebaliknya. Mereka melihat potensi luar biasa. Terbukti, kini Rizal adalah salah satu guard-forward terbaik di liga basket profesional kita. Mudah bagi para pelatih Australia untuk melihat potensi Rizal, tetapi sulit bagi saya. Di sinilah para pelatih Australia itu memainkan perannya.
Lalu ada Gradita. Ia ikut DBL Camp. Saya lupa tahun berapa tepatnya. Tetapi saya ingat dia tak bisa menuntaskan camp karena cedera. Dita bahkan harus menyaksikan teman-temannya dari tepi lapangan sambil duduk di kursi roda.
Namun sebelum cedera, Dita sudah memperlihatkan bakat besarnya yang sudah tidak mungkin diabaikan. Walau cedera, ia terpilih masuk All Star. Selanjutnya, Dita adalah point guard Indonesia yang meraih perak di SEA Games Singapura tahun lalu.
Ok, untuk jawaban kedua, âtidakâ!
Benar, tidak mudah memang menentukan 24 pemain terbaik dalam waktu empat hari. Ok, maksudnya âhampir- tidak mungkin (dalam beberapa kasus).
Terlepas dari beberapa pelatih berpengalaman yang menangani DBL Camp, sangat ada peluang mereka (pelatih Australia dan Indonesia) melakukan kesalahan atau melewati satu-dua pemain hebat. Walau saya tetap merasa kemungkinan ini sangat kecil. Kalau pun terjadi, dan memang pernah terjadi, berikut beberapa penyebab atau hal-hal yang terjadi di sekitarnya.
Banjir potensi di satu posisi.
DBL All Star hanya memilih 12 pemain. Dari 12 pemain ini, mereka terbagi merata ke dalam masing-masing lima posisi bermain. Ada point guard (posisi 1), shooting guard (2), small forward (3), power forward (4) dan center (5).
Perdebatan di ruang pemilihan pemain seringkali terjadi ketika ada banyak pemain bagus di satu posisi saja. Misalkan, ada enam point guard bagus, sementara yang dibutuhkan hanya tiga.
Pemain-pemain yang hanya baik sebagai point guard biasanya akan tersingkir. Pemain yang memiliki kemampuan bermain di posisi 1 baik dan bisa menembak (2) akan memiliki peluang besar untuk lolos.
Hal serupa ini juga kerap terjadi bila di sebuah posisi malah kekurangan pemain. Misalnya, posisi center butuh tiga pemain. Tetapi yang benar-benar layak hanya satu. Maka sangat mungkin dua lainnya adalah pemain yang memiliki postur center (tinggi-besar-bertenaga) tetapi belum begitu bagus secara teknik bermain. Posisi ini hampir tidak mungkin diisi oleh pemain posisi 1 yang tersingkir, meskipun ia sangat-sangat baik. Karena kalau dipaksakan, tim yang terbentuk akan pincang.
Jadi, pemain sehebat apa pun, kalau posisi bermainnya tidak dibutuhkan, ya sangat mungkin tidak terpilih masuk skuat All Star.
Pilihan bisa juga terasa keliru ketika tim sudah terbentuk.
Maksudnya begini,
Ketika sudah terbentuk menjadi sebuah tim All Star, mereka akan menjalani beberapa pertandingan. Baik sebelum ke Amerika Serikat, maupun saat ada di AS. Dalam pertandingan-pertandingan inilah saya kemudian bisa melihat bahwa beberapa pemain seperti âmenghilangâ kemampuannya.
Entah apa yang terjadi. Apakah kehilangan motivasi karena sudah terpilih atau merasa besar kepala sehingga tidak perlu lagi menunjukkan kemampuan terbaiknya. Saat itulah, saya dan beberapa panitia di DBL menepuk jidad sambil mengeluh, âAndai dulu si B yang terpilih, bukan si A.â
Namun kejadian ini jarang terjadi. Kalau pun terjadi, hanya satu pemain saja per angkatan. Seingat saya, tak pernah sampai ada dua pemain yang potensinya menurun setelah terpilih All Star.
Kasus lain bahkan terjadi jauh sebelum DBL Camp. Para penyeleksi sangat mungkin melewatkan beberapa bakat hingga mereka tak terpilih masuk First Team alias bergabung di DBL Camp.
Contoh yang paling saya ingat adalah Hardianus. Hardianus bermain di DBL, tetapi tidak masuk jajaran First Team dan oleh karenanya tidak berangkat ke Surabaya untuk ikut DBL Camp.
Belakangan, Hardianus berkembang menjadi salah satu point guard terbaik di Indonesia. Hardi bahkan menjadi juara NBL Indonesia bersama Satria Muda Jakarta di tahun 2015.
Lalu ada Muhammad Dhiya Ulhaq. Dhiya ikut Camp, tetapi tak masuk skuat All Star. Belakangan, Dhiya kemudian direkrut oleh tim profesional Garuda Bandung dan menjadi center kuat di sana. Dhiya bahkan meraih medali emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) 2012 bersama kontingen Jawa Barat.
Berkaca pada dua kasus tersebut, maka ya, bisa dikatakan DBL Camp gagal menjaring bakat-bakat hebat.
Tetapi, DBL memiliki klausa penyelamat untuk kasus-kasus istimewa tersebut. Di ujung Farewell Party, ketika 12 pemain terbaik putri dan putra sudah terpilih, DBL selalu mengeluarkan kalimat singkat, âBuktikan, bahwa kami keliru dalam memilih.â
Maka karenanya, yang bersinar di kemudian hari tanpa terpilih menjadi DBL All Star adalah mereka yang membuktikan bahwa DBL Camp pernah keliru dalam memilih.
Sebelum menjadikan bahwa tulisan ini adalah opini saya semata, kemarin saya mencoba menanyakan hal serupa kepada Andrew Vlahov, ketua tim pelatih Honda DBL Camp yang juga legenda basket Australia yang sudah main di empat olimpiade.
Vlahov sepakat bahwa tidak ada sistem yang sempurna.
âSelalu ada ruang untuk berkembang. Saya dan tim pun selalu mendiskusikan apakah sistem yang telah kita jalani selama enam tahun terakhir ini adalah sistem yang terbaik. Kami menemukan beberapa kelemahan yang selalu kami coba cari solusinya. Jadi, ya, bagi saya, masih banyak ruang untuk berkembang,â kata Vlahov.
Ya, tidak ada sistem yang sempurna memang. Jangankan DBL Camp yang hanya empat hari, Amerika Serikat (baca: NBA) yang memiliki sistem kompetisi terbaik di level universitas dan sekolah menengah yang harus dilewati oleh pemain selama bertahun-tahun juga kerap keliru memilih pemain terbaik.
Tak percaya, silakan lihat berapa pemain pilihan pertama di Draft NBA yang ujung karirnya biasa-biasa saja. Atau sebaliknya, berapa banyak yang awalnya tak diperhitungkan, malah kemudian bersinar bahkan menjadi pemain legendaris.
Contoh paling nyata adalah Kobe Bryant. 12 tim NBA tidak meliriknya. Charlotte Hornets memilih Kobe pada kesempatan memilih ke-13. Itu pun untuk 'dibuang' ke Lakers. Lihat apa yang terjadi pada Kobe saat ini.
Bila NBA saja bisa melakukan kekeliruan yang nyata, apatah artinya DBL ini yang tak seujung kuku mereka. (*)
























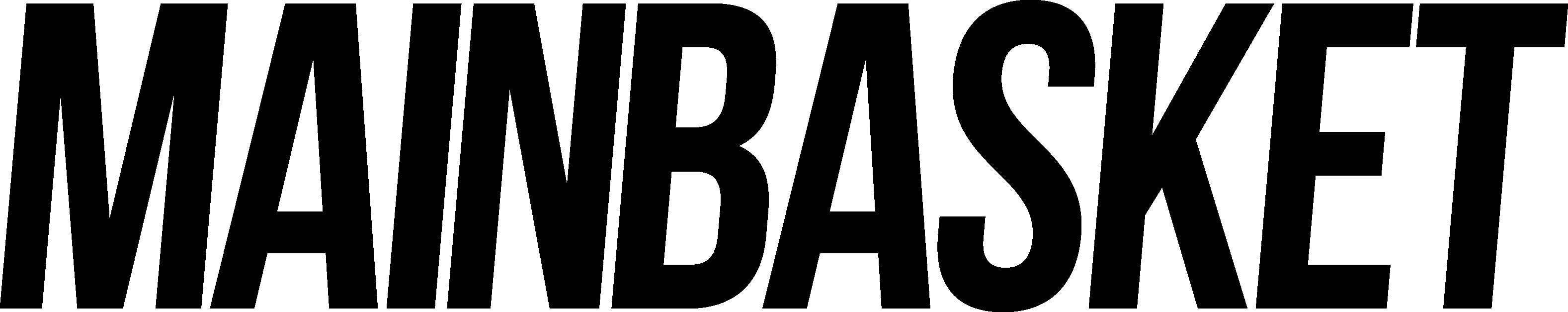




 0822 3356 3502
0822 3356 3502