Saya ingat betul pertama kali kedua orang tua saya pergi menonton pertandingan basket secara langsung.
Saat itu, saya masih SMP kelas VII. Salah satu SMA di Kota Jember mengadakan pertandingan basket antar-SMA dan SMP. Sekolah saya menjadi salah satu pesertanya.
Jadwal pertandingan saya dilaksanakan pada sore hari. Beberapa jam sebelum pertandingan, saya berpamitan kepada kedua orang tua.
Saya izin pergi latihan basket.
Ya, saya mendatangi pertandingan basket, tetapi malah izin pamit kepada kedua orang tua untuk latihan basket seperti biasa.
Sesampainya di lapangan, tampak para panitia pelaksana menyiapkan segala peralatan pendukung pertandingan. Saya bertemu beberapa teman satu tim. Kami bersenda gurau layaknya anak pada umumnya.
Mendekati jam dimulainya pertandingan, saya bersiap-siap memakai sepatu olahraga, juga mengganti baju dengan jersey tim sekolah; melakukan pemanasan lebih awal; hingga tanpa saya sadari kedua orang tua saya datang mendekat.
Sontak saya terkejut saat menyadari kedatangan mereka.
,_Brian_Rowsom_(Head_Coach),_Koko_Heru_Setyo_Nugroho_(asisten_pelatih).jpg)
Saya kaget sekaligus malu, sebenarnya.
Kaget karena, kok, bisa Bapak dan Ibu tahu kalau saya akan bertanding? Saya, kan, berpamitan untuk latihan basket.
Lalu, kenapa harus malu? Apa salahnya dengan orang tua yang ingin menonton anaknya bertanding?
Ya, saya malu.
Bukan malu dalam arti karena tidak pandai bermain basket, hingga nantinya akan mempermalukan kedua orang tua di hadapan orang lain, tetapi lebih buruk dari itu.
Saya malu. Saya malu kepada teman-teman. Saya malu jika mereka harus melihat orang tua saya. Sosok orang tua sederhana dari keluarga yang tidak “berpunya”.
Bisa dibilang, Bapak dan Ibu saya orang miskin. Saya malu karena dilahirkan dari orang tua yang miskin di tengah teman-teman sekolah yang serba kecukupan. Saya membandingkan diri dengan teman-teman yang lain.
Coba tebak, apa yang selanjutnya terjadi?
Saya, Arif Hidayat, bocah yang tidak tahu diri ini menyuruh Bapak dan Ibu pulang. Saya bahkan memohon dengan sedikit memaksa kepada mereka untuk pulang. Saya tidak ingin mereka menonton pertandingan basket karena saya malu.
***
Sejak saya merantau ke Surabaya, pemikiran saya tentang sosok orang tua berubah.
Hidup mandiri di luar kota secara tidak langsung membuka wawasan saya. Pertemuan dengan banyak orang, lingkungan, dan gaya hidup baru membuat saya mampu menelaah banyak hal. Saya belajar tentang apa saja yang baik dan yang tidak seharusnya dilakukan.
Di kota ini saya juga bertemu dan berteman dengan banyak orang dari berbagai golongan. Mulai dari mereka yang rajin kuliah sampai tukang titip absen. Ada yang malam minggunya dihabiskan untuk pergi ke klub malam. Ada pula yang hanya berdiam diri di dalam kamar.
Di Surabaya, jauh dari keberadaan orang tua membuat perasaan rindu yang dulunya tidak pernah ada, tanpa saya sadari kini kerap muncul. Terkadang saya merindukan perintah-perintah Ibu untuk menyapu, mengepel lantai, atau menyuci piring. Saya merindukan teriakan Ibu saat memarahiku karena sesuatu.
Saya juga merindukan Bapak yang cukup sering mengingatkan untuk makan ikan laut. Kata beliau, ikan laut membuat saya pintar.

Berada di perantauan membuat saya merindukan kehadiran Bapak dan Ibu. Itu sebabnya saya jadi menghargai setiap waktu yang saya lalui bersama mereka. Saya yang dulu hanya berbicara kepada Ibu saat meminta uang SPP, kini justru seperti anak balita yang sedang manja kepada orang tua.
Saat pulang ke Jember, saya juga bisa menemani Bapak untuk jalan pagi. Beliau memang rutin melakukan itu. Kemudian, sepulangnya jalan pagi, saya bisa langsung membantu Ibu untuk memasak di dapur.
Orang tua saya tidak banyak ikut campur dengan pilihan-pilihan yang diambil anak-anaknya. Mereka tipe orang tua yang membebaskan kehendak anak-anaknya. Asalkan apa yang kami lakukan itu baik. Itu sebabnya orang tua mengizinkan saya untuk hidup jauh dari mereka.
Hidup seorang diri secara tidak langsung memaksa saya harus mandiri. Saya harus mengatur semuanya sendiri. Entah itu soal waktu bermain bersama kawan, jadwal kuliah, sampai keuangan pribadi. Saya merasakan bagaimana susahnya mencari uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Seketika itu, ingatan-ingatan tentang saya yang merengek; menuntut barang A-B-C kepada orang tua, berputar kembali. Padahal saya tahu kondisi keuangan keluarga saya serba kekurangan. Namun, saya selalu merengek menginginkan barang-barang itu hanya karena teman-teman lain mengenakannya.
Perasaan bersalah itu menyiksa saya. Dari situlah saya mulai berpikir: saya ingin melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati kedua orang tua.
***
Awal saya bergabung dengan tim senior CLS Knights, sesekali orang tua saya pergi untuk menonton pertandingan secara langsung. Saat mereka menelepon dan mengutarakan keinginan menonton, saya mengiyakannya. Padahal saat itu, dalam hati kecil saya, masih ada keengganan.
Perasaan malu sebenarnya masih menghantui saya.
Lucunya, saat Bapak dan Ibu kembali pulang ke Jember, perasaan bersalah muncul. Itu menyiksa saya. Saya pun mencoba meyakinkan diri bahwa tidak ada salahnya dengan orang tua yang ingin menonton pertandingan anaknya secara langsung.
Saya mencoba belajar melihat sudut pandang lain. Saya memposisikan diri sebagai mereka, sebagai orang tua.
Jika saya adalah mereka, tentunya saya akan senang dan bangga melihat anak—yang dirawatnya sedari kecil sampai akhirnya beranjak dewasa—berada di sebuah arena, dalam sebuah pertandingan yang ditonton banyak orang.
Orang tua mana yang tidak bangga?

Bagi saya, pergi ke Surabaya, mungkin, sesuatu yang biasa. Namun, itu berbeda bagi kedua orang tua saya. Mengunjungi Surabaya bagi mereka layaknya bertamasya ke kota impian. Saya bisa melihat kebahagiaan itu di wajah mereka.
Untuk inilah saya ingin hidup: membahagiakan kedua orang tua.
Saat merasakan rasa bahagia itu, saya jadi tidak ingin mati muda. Saya ingin terus merasakan kebahagiaan itu. Saya ingin orang tua saya melihat saya bermain basket seperti yang mereka inginkan saat saya masih SMP. Saya ingin terus melihat raut wajah bahagia mereka selepas menonton pertandingan.
Kedua orang tua saya kini jadi salah satu alasan kenapa saya masih bermain basket. Saya ingin menghibur mereka; membanggakan mereka dengan prestasi saya dalam dunia basket.
Detik ini, saya bangga lahir dari kedua orang tua yang sederhana. Dari mereka, saya belajar apa itu kerja keras.
Suwon, Pak, Bu!
Foto: Dok. Arif Hidayat, Yoga Prakasita, dan Yosi R.

























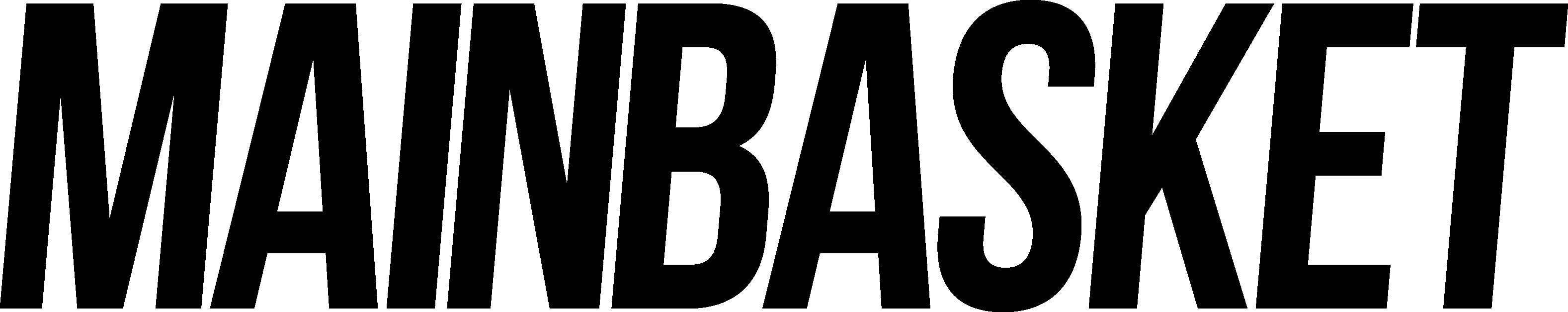




 0822 3356 3502
0822 3356 3502